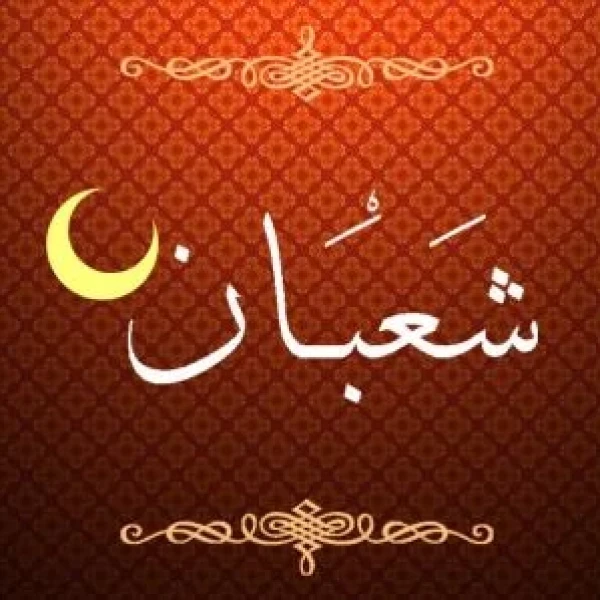Akad Rusak: ‘Awalnya Bersama-sama kok Ujungnya Jadi Milik Pribadi?’
Rabu, 6 Januari 2021 | 06:47 WIB
Redaksi Banten
Penulis
Manusia sebagai makhluk sosial memang tidak bisa meninggalkan masyarakat. Sedikit atau banyak, ia tetap membutuhkan uluran dan bantuan orang lain. Ia juga tetap membutuhkan kerja sama dengan orang lain dalam mengentaskan hajat hidupnya.
Contoh kecil, untuk mendapatkan barang yang hendak dipergunakan bersama (mal syuyu’), misalnya pipa atau paralon untuk mengalirkan air dari mata air tertentu, umumnya pihak yang terlibat dalam kebutuhan air memaksakan diri bergotong royong swakarsa urunan membeli pipa tersebut.
Tentu tindakan ini adalah tindakan yang bagus, mengingat masyarakat kita adalah masyarakat yang senantiasa berpegang pada adat ketimuran, yaitu gemar bergotong royong. Ada unsur ta’awun (tolong menolong) yang terlibat di dalamnya, tanpa adanya tendensi apa pun. Yang terpenting bagi masyarakat ini adalah air segera bisa mengalir ke rumah-rumah warga.
Permasalahannya adalah saat ada introduksi teknologi terbaru, sehingga masyarakat berlomba-lomba mengambil air dari jalur baru dan meninggalkan teknologi lama berupa saluran yang dibangun secara bersama-sama. Di sinilah terkadang tindakan penguasaan sepihak terhadap aset bekas saluran lama itu terjadi.
Seharusnya, jika diselesaikan secara fiqih, keberadaan aset lama itu menghendaki pemecahan masalah secara adil, yaitu pembagian aset bekas saluran air secara bersama-sama. Mengapa? Sebab aset itu dibangun dan dibiayai secara bersama-sama oleh masyarakat.
Hak pihak yang pernah ikut urun dalam mewujudkan saluran air harus senantiasa diperhatikan, dan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan, apa pun wujudnya. Ketiadaan pengembalian hak merupakan bagian dari sikap idlrar (merugikan pihak lain). Hukumnya adalah haram.
Jika pengembalian hak ini tidak memungkinkan, dan memaksa harus ada salah satu pihak yang mengakuisisinya, maka pihak yang mengakuisisi wajib memberikan ganti rugi (arsyun) terhadap semua aset yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya, ganti rugi (dlaman) itu diberikan ke setiap peserta urun, tanpa kecuali.
Sikap mengakuisisi aset bekas secara sepihak tanpa adanya langkah-langkah yang dibenarkan secara syara’ dalam menguasainya, dapat disamakan dengan tindakan meng-ghashab. Mengapa?
Sebagaimana kita ketahui bahwa penguasaan (istila’) barang/hak milik orang lain yang asalnya disepakati sebagai harta bersama (musyarakah), tanpa seizin pihak lain yang juga turut berhak atas barang tersebut, adalah istilah lain daripada ghashab.
Contoh praktis lainnya adalah: ada dua mahasiswa bersama-sama membeli sebuah buku paket pelajaran yang diwajibkan oleh dosennya secara patungan. Di akhir semester, tiba-tiba buku dikuasai oleh salah satu pihak yang melakukan patungan, tanpa adanya ganti rugi (arsyun).
Nah, penguasaan semacam ini adalah tidak sah. Pihak yang menguasai terikat sebuah keharusan, yaitu mengganti harga buku tersebut sesuai nisbah harga mitsil yang berlaku saat akuisisi itu dilakukan. Jadi, misalnya harga loak buku itu adalah sebesar 50 ribu rupiah, sementara patungannya adalah masing-masing menyetor 50 ribuan sehingga harga awalnya 100 ribu rupiah, maka harga akuisisi (syuf’ah) yang harus dikeluarkan oleh salah satu syarik (mitra) adalah sebesar 25 ribu rupiah. Alhasil, mengetahuhi harga mitsil (standar) itu sangat penting dalam konteks ini, sebagai dasar penguasaan.
Beberapa pihak juga ada yang menyatakan, bahwa bukankah umumnya masyarakat tidak mempedulikan sisa bekas saluran air itu? Pertanyaan semacam ini kerap muncul, sehingga menjadikan seseorang bersikap menggampangkan dalam mengakuisisi.
Sebenarnya sikap seperti ini lahirnya juga bukan serta merta dari pihak yang mengakuisisi. Masyarakat sendiri terkadang segan untuk mengusik dan melakukan perhitungan. Akibatnya, dalam kasus-kasus serupa, namun berskala besar, mereka acap menjadi korban keserakahan pihak pengakuisisi.
Bila muncul pertanyaan semacam di atas, kita seyogianya adalah mengembalikan pada kewajiban yang melekat dan berlangsung tsubut atas pengakuisisi harta (syafi’). Bagamanapun juga aset saluran air itu, meskipun merupakan barang bekas, tetaplah merupakan harta. Langkah penguasaannya harus tetap bisa dipertanggungjawabkan secara syara’ dengan orientasi utama, yaitu thayyibi al-anfus (pengambilan hak secara enak dan tidak menimbulkan potensi permasalahan di belakang hari).
Itulah sebabnya, di dalam fiqih, langkah untuk mengakuisisi barang musyarakah tersebut diatur sedemikian rupa dan hukumnya adalah wajib, khususnya dalam mazhab Syafi’i. Anda bisa menemukan penjelasan ini di berbagai kitab rujukan fiqih mazhab Syafi’i.
Maksud dari wajib di sini adalah tidak bisa tidak, proses itu harus dilakukan. Melakukannya ini baik terhadap barang yang bisa dibagi, atau bahkan terhadap barang yang tidak bisa dibagi. Akadnya dinamakan sebagai akad syuf’ah.
Ketiadaan akad syuf’ah, menjadikan penguasaan hak terhadap aset bekas tersebut dapat dipandang sebagai praktik ghashab yang merupakan bagian dari dosa besar (mina al-kabair). Mengapa? Sebab ada bagian pihak lain yang dikuasai secara tidak sah.
Akan tetapi, bukankah pihak mitra juga sudah turut merasakan manfaatnya?
Pertanyaan ini kerap dijadikan dalih oleh pihak pengambil alih barang sebagaimana dicontohkan. Pihak pengambil alih kepemilikan ini seolah menyatakan bahwa manfaat yang sudah diterima oleh mitra, jauh-jauh hari sebelumnya adalah termasuk ujrah (upah).
Jika manfaat yang didapat oleh syarik sebelumnya dianggap sebagai sebuah relasi akad ijarah dengan pihak yang mengambil alih aset, maka akad ijarah semacam ini adalah termasuk akad ijarah fasidah (rusak/tidak sah). Alhasil, penyelesaiannya, pihak pengambil alih aset harus mengganti seluruh biaya pembelian selang (pipa air), sesuai dengan besar iuran pembelian saluran paralon air itu dibebankan kepada masyarakat selaku mitra.
Adapun, kerugian pipa yang sudah dibeli itu juga menghendaki penyelesaian berupa pemberian biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pihak penguasa aset. Di sisi lain, masyarakat dikenakan beban pembelian air setiap bulannya, yang semuanya juga wajib dihitung sebagai ujrah mitsil.
Demikianlah, apa yang disampaikan oleh penulis di atas hanyalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan adanya pola pengelabuan akad yang rawan disalahgunakan untuk menipu masyarakat. Ilustrasi ini bisa kita tarik pada kasus yang besar, seumpama pendirian koperasi, atau bahkan perusahaan. Kelak, kita akan sampaikan di tulisan lain. Wallahu a’lam bish shawab.
Penulis : Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jatim
Terpopuler
1
Dilantik Katib 'Aam PBNU, Berikut Susunan Lengkap PWNU Banten 2025-2030
2
Dzikir-Doa dari Cempaka Putih, Isi Kemerdekaan dengan Penguatan Spritual
3
Ribuan Warga NU Siap Hadiri Pelantikan PWNU Banten 2025-2030
4
Ketua PCNU Lebak: Berkhidmat di NU Adalah Mondok
5
Jadi Santri Itu Harus Terus Bergerak dan Menggerakan Supaya Berkah
6
Muslimat NU Menjaga Keluarga, Masyarakat, dan Negara
Terkini
Lihat Semua