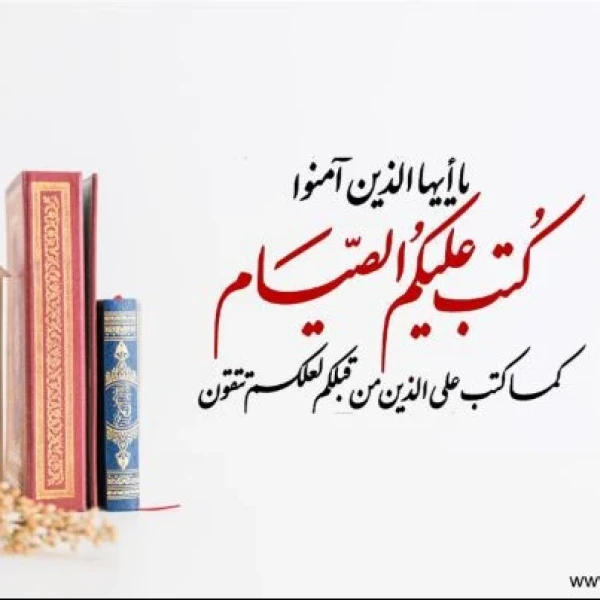Saban kedatangan Bulan Suci Ramadhan, hendaknya perlu disyukuri sekaligus kontemplasi. Lebih-lebih, hingga hari ini, kita belum terbebas ujaran kebencian, hoaks, dan dakwah provokatif-intoleran. Nuansa damai hidup bersama seperti barang mahal.
Baca Juga
Menakar Toleransi saat Ramadhan
Pun, aneka praktik banalitas berkedok agama telah menyayat ketentraman. Tujuannya tak lain tak bukan untuk mengusik dan memporak-porandakan masyarakat yang multikultur; agar saling menaruh rasa curiga. Dalam kondisi seperti ini, akal sehat dan kewarasan tetap wajib dikedepankan. Penonjolan emosi bisa-bisa menyebabkan kondisi bertambah runyam. Kutukan terhadap laku biadab macam teror memang mesti kita gaungkan. Kita pun mesti memproklamirkan sikap untuk melawan praktik intoleran.
Karena tujuan intoleransi untuk menyebar agitasi-ketakutan dan permusuhan di antara sesama, justru berangkat dari sini, kita pun seyogianya berpikir kritis bahwa, kita tidak boleh terprovokasi. Meyakini bahwa agama tidak sama sekali mengajarkan laku intoleran dan teror. Saban diri kita sebagai umat beragama perlu sejenak berkontemplasi untuk kemudian bisa memunculkan gugatan reflektif bahwa, kalau agama memang mengajarkan intoleransi apalagi terorisme, tentulah dunia ini beserta umat manusia sudah hancur-punah sejak dahulu. Kita pun harus meyakini bahwa para teroris hanya berpikir absurd dan paradoks. Mereka, para teroris, kerap mengatasnamakan agama. Padahal, yang diatasnamakan alias agama itu sendiri nyata-nyata tidak membenarkan.
Kita mengapresiasi kerja aparat hukum yang belakangan sigap dalam upaya pemberantasan terorisme. Kita mafhum perihal akibat perbuatan para teroris dengan melakukan tindak destruktif, terbukti mengakibatkan cacatnya/lenyapnya orang-orang yang tidak berdosa/tidak mempunyai kepentingan apa pun. Nyata-nyata, korban intoleransi dan terorisme bisa menimpa siapa saja. Baik anak kecil hingga yang tua renta. Baik pengusaha besar hingga pedagang asongan, semua merasakan efek dahsyat tindakan teror. Dan, imbas terorisme juga tidak mengenal pemeluk agama tertentu. Semua lapisan masyarakat beserta identitas primordial dan atribut keagamaan, semuanya merasakan keganasan terorisme. Jadi, ketika ada pemboman, kita memang harus mengatakan bahwa aksi teror tidak ada kaitan/identik dengan agama apa pun sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo saat menanggapi teror bom di Makassar, awal April 2021 lalu.
Praktik intoleransi dan bibit terorisme bermula dari paham ekstremisme beragama. Karena itu, terutama di media sosial, kesadaran reflektif masyarakat perlu mesti disinkronkan dengan gerak lincah jemari. Jangan sampai cuitan maupun unggahan di Twitter dan Facebook mengarah pada desakralisasi nama suci agama. Melainkan, sikap untuk menibakan intisari ajaran agama dalam hal ajaran welas asih dan saling toleransi untuk disorongkan semaksimal mungkin; sebagai ruang membangun kesolidan solidaritas. Khazanah agama yang dipeluk masyarakat Indonesia mestinya menjadi tameng dan perisai dari segala tindakan teror dan adu domba.
Namun, memang kita tidak bisa menyangkal bahwa, ada sebagian kecil pihak dengan cara beragama mengarah radikalisme-ekstremisme. Kita mafhum, ekstremisme seperti duri dalam daging. Tidak saja mengusik intisari kerukunan internal pemeluk suatu agama, tetapi juga lantang menafikan eksistensi agama lain. Sehingga, ujung atas paham ekstremisme adalah hanya dirinya saja yang benar. Padahal, prinsip agama merupakan jalan tengah (wasathiyyah) sekaligus sebagai metode pencerahan manusia merajut harmoni dalam mengelola bumi ini.
Memasuki Ramadan, syahru al-shiyam, merupakan momen sakral untuk sejenak bermenung perihal esensi ibadah puasa. Spirit puasa terletak pada ikhtiar jiwa dan raga untuk cakap dan mumpuni dalam pengendalian diri. Pada pemaknaan mendasar, puasa merupakan ajang pengendalian diri untuk tidak makan tidak minum semenjak pagi hingga petang. Namun, oleh Baginda Nabi SAW, model puasa dengan sekadar pengendalian urusan perut macam itu, tidak memperoleh pahala sama sekali kecuali hanya mendapat rasa lapar dan dahaga. Sementara kebermaknaan puasa lebih kepada pengendalian jiwa, hati, dan pikiran. Sehingga produk puasa adalah menghasilkan pribadi bertakwa; pribadi santun, berperangai luhur.
Ditilik mendalam, ritus puasa --yang juga ditemukan di hampir setiap agama, menorehkan maksud untuk senantiasa bersikap bijak. Karena itu, puasa sebagai ajang pengendalian jiwa bisa menjadi cara ampuh mengobati pemahaman ekstremisme. Pada diri orang berpuasa, semestinya terbuncah rasa mengendalikan diri untuk tidak gampang menyalahkan orang lain. Seyogianya juga memunculkan sikap kendali diri untuk tidak merasa benar sendiri dalam beragama. Pada perut lapar dan tenggorokan haus, mestinya menghasilkan rasa kemengertian dan welas asih terhadap sesama; kesamaaan derajat sebagai hamba Tuhan.
Pada ibadah puasa, jiwa dan raga benar-benar digembleng. Sebagaimana petuah Nabi SAW di atas, maka terkata percuma bila diri ini berpuasa, tetapi tidak bisa mengendalikan jemari untuk memposting ujaran kebencian, provokasi, dan hoaks. Pikiran dan hati masih diliputi kecurigaan dan sinisme terhadap liyan. Momentum Ramadhan merupakan titik tolak mengubah sikap destruktif tersebut berganti dengan mencuitkan dan men-sharing konten-konten kebajikan. Inilah kiranya pemaknaan berpuasa di era gadget macam hari ini.
Refleksi berpuasa adalah agar ritus beragama tidak sekadar menggugurkan kewajiban. Melainkan pula mampu merembes dalam kehidupan sehari hari sepanjang waktu. Ada pesan menghunjam dari kaum bijak bestari sebagai bahan perenungan, yakni: shalatlah setelah salam dan berpuasalah selepas berbuka. Wallahu a’lam
Muhammad Itsbatun Najih, Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terpopuler
1
Krisis Kepemimpinan, Manajemen Konflik, dan Budaya Malu
2
MWCNU Larangan Dilantik, Dorong Sinergitas dan Kemandirian Jam’iyah
3
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Presiden Tak Peka Keresahan Rakyat
4
Akademisi Australia Ini Sebut Gus Dur Jadikan Islam Lebih Kontekstual
5
Redam Amarah Rakyat, ISNU Tangsel Desak Segera Disahkan RUU Perampasan Aset
6
Kepada Aparat Penegak Hukum, Ini Pesan Rektor UIN Jakarta
Terkini
Lihat Semua